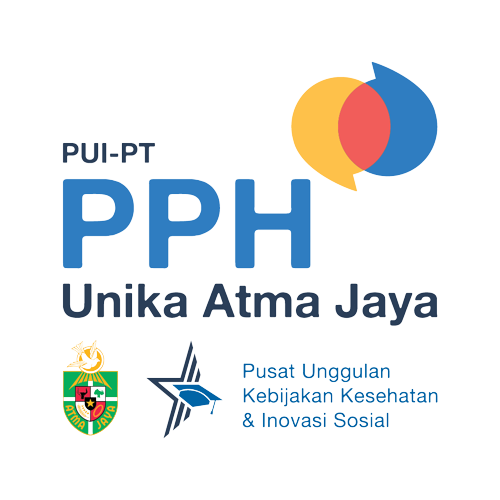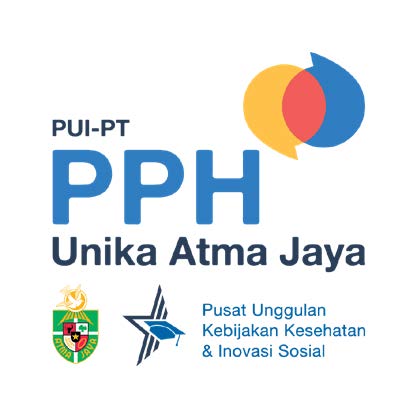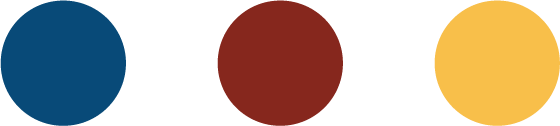Beberapa hari yang lalu saya membaca potongan artikel dari postingan seorang dosen di akun facebook-nya yang menyebutkan bahwa kasus HIV pada anak muda merupakan akibat dari pergaulan bebas. Tentunya setiap orang berhak untuk berpendapat, dan mungkin bagi sebagian besar orang, tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut. Namun, hal tersebut membuat saya bertanya-tanya. Mengapa saya merasa bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar? Haruskah kejadian atau penularan dari suatu penyakit dihubungkan dengan perilaku yang dicap negatif oleh masyarakat?
Tiba-tiba saya teringat dengan pertanyaan dari salah seorang teman pada saat mengetahui bahwa saya bekerja di Pusat Penelitian HIV AIDS, “Apakah kamu tidak takut tertular HIV karena sering bertemu dengan penderita HIV? Apakah penderita HIV dapat bertahan hidup?” Saya tertawa dalam hati saat mendengarkan pertanyaannya sembari berpikir untuk dapat memberikan jawaban yang mudah dimengerti tetapi tetap berasal dari sumber terpercaya.
Salah satu penjelasan yang saya rasa akan paling mudah dimengerti untuk menjawab pertanyaan tersebut datang dari penjelasan World Health Organization. Seseorang tidak akan terinfeksi HIV dengan bersentuhan, bergandengan tangan, berpelukan, menggunakan alat makan dan minum yang sama, bahkan berciuman dengan orang yang hidup dengan HIV (World Health Organization, 2020). Penularan HIV tidak segampang yang orang-orang pikirkan. Selain itu, dari pengamatan saya, mereka yang hidup dengan HIV bukan hanya dapat bertahan hidup, bahkan sebagian dari mereka bisa hidup lebih produktif dibandingkan sebagian orang yang tidak hidup dengan HIV.
Saya tidak menyalahkan teman saya karena pertanyaan yang ia ajukan. Saya berasumsi bahwa tidak semua orang memiliki pengetahuan yang memadai tentang HIV. Apalagi bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan non-kesehatan dan tidak pernah terpapar dengan informasi terkait HIV AIDS. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 bahkan menunjukkan bahwa empat dari sepuluh penduduk Indonesia yang berumur ≥ 15 tahun belum pernah mendengar tentang HIV AIDS. Di antara mereka yang pernah mendengar tentang HIV AIDS, terlihat rendahnya proporsi masyarakat yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV AIDS (Kemenkes RI, 2019). Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap HIV AIDS sangat disayangkan, mengingat di zaman sekarang informasi apapun dapat kita peroleh hanya dengan sekali sentuh, termasuk informasi mengenai HIV AIDS.
Setelah mengulik lebih jauh data Riskesdas 2018, fakta lain saya jumpai. Masyarakat Indonesia tidak hanya memiliki pengetahuan yang masih kurang terkait HIV AIDS, tetapi juga masih menunjukkan stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV. Prevalensi sikap menstigma terhadap orang dengan HIV ditunjukkan oleh hampir 60% responden. Para responden menyatakan bahwa mereka tidak akan membeli sayur dari petani atau penjual yang diketahui terinfeksi HIV AIDS dan hampi 40% responden menyetujui agar guru yang terinfeksi HIV AIDS tidak diperkenankan untuk mengajar (Kemenkes RI, 2019).
Pertanyaan yang mungkin diajukan oleh sebagian orang selanjutnya adalah, “Apa itu Stigma?”
Istilah “stigma” berasal dari bahasa Yunani, mengarah pada tanda-tanda pada tubuh yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang tidak biasa atau sesuatu yang buruk tentang status moral seseorang. Goffman (1963) untuk pertama kalinya mendefinisikan stigma sebagai proses dinamis dari penurunan nilai sebagai suatu sifat yang sangat menyudutkan atau mendiskreditkan seorang individu dimata orang lain. Link & Phelan (2001) mendefinisikan stigma sebagai pertemuan dari empat komponen yaitu pelabelan, stereotipe, pemisahan, penghilangan status dan diskriminasi. Stigma karena suatu penyakit menjadi dasar seseorang untuk mengklaim bahwa orang dengan penyakit tertentu berbeda dari kondisi “normal” dalam masyarakat, tidak hanya dipandang sebagai infeksi dari satu agen penyebab penyakit (Deacon dkk., 2005). UNAIDS (2005) menggambarkan stigma terkait HIV sebagai suatu proses penurunan nilai dari orang yang hidup dengan HIV atau mereka yang berhubungan dengan HIV AIDS (pasangan, keluarga, dan populasi kunci), dengan perlakukan diskriminatif yang tidak wajar dan tidak adil berdasarkan status HIV-nya (real & perceived).
Stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV terjadi dimana saja, baik dalam setting keluarga, tempat kerja, sektor pendidikan, sistem peradilan, bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan (UNAIDS, 2018). Dan pada kenyataannya, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV AIDS jauh lebih mengerikan daripada infeksi virusnya.
Dalam setting keluarga, stigma dan diskriminasi tampak dari tindakan anggota keluarga lainnya yang menolak untuk berbagi makanan atau peralatan makan, bahkan ada yang tidak menerima atau menjauhi anggota keluarganya yang diketahui terinfeksi HIV. Di banyak negara, orang yang hidup dengan HIV sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi pekerjaan karena status HIV-nya. Hilangnya kerahasiaan status HIV juga menjadi isu utama dari adanya kebijakan pemeriksaan kesehatan yang wajib dilakukan di tempat kerja. Anak-anak dan remaja yang hidup dengan HIV dapat dengan mudah dikeluarkan dari sekolah. Mereka mengalami diskriminasi dalam pengaturan tempat duduk, penolakan saat bermain bersama, bahkan pelecehan fisik yang menyebabkan rendahnya partisipasi mereka dalam belajar. Dari segi hukum, terdapat kebijakan yang cenderung mendiskriminasi orang yang hidup dengan HIV, seperti pemeriksaan HIV yang wajib untuk ibu hamil. Pengadilan juga dapat melanggar kerahasiaan pasien dengan menggunakan catatan pengobatan sebagai bukti. Di sektor kesehatan, masih terdapat tenaga kesehatan yang memiliki sikap negatif terhadap orang yang hidup dengan HIV, membuka status tanpa sepengetahuan pasien, menghindari kontak fisik, dan bahkan ada yang menolak untuk memberikan pelayanan kepada orang yang hidup dengan HIV (UNAIDS, 2018).
Pada hakikatnya, semua bentuk stigma dan diskriminasi menyebabkan orang yang hidup dengan HIV atau terdampak dengan HIV tidak dapat memperoleh hak-nya. Hasil penelitian membuktikan bahwa stigma dan diskriminasi menghambat akses terhadap layanan kesehatan, mencegah pemeriksaan dan pengobatan HIV sedini mungkin, mengurangi kepatuhan dalam mengkonsumsi obat antiretroviral (ARV), dan memperburuk kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV AIDS (Holzemer et al., 2009; Katz et al., 2013; Gesesew et al., 2017). Seiring berjalannya waktu, stigma dan diskriminasi telah menjadi katalisator peningkatan angka kesakitan dan kematian HIV AIDS di seluruh dunia dan sampai hari ini masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya mengakhiri epidemi HIV sebagai masalah kesehatan global.
Reference
Deacon, H., Stephney, I. and Prosalendis, S. (2005) Understanding HIV/AIDS Stigma: A theoretical and methodological analysis.
Gesesew, H.A., Tesfay Gebremedhin, A., Demissie, T.D., Kerie, M.W., Sudhakar, M. and Mwanri, L. (2017) Significant association between perceived HIV related stigma and late presentation for HIV/AIDS care in low and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. PloS one, 12(3), p.e0173928.
Goffman, E. (1963) Stigma: notes on the management of a spoiled identity. New York: Simon and Schuser
Holzemer, W.L., Human, S., Arudo, J., Rosa, M.E., Hamilton, M.J., Corless, I., Robinson, L., Nicholas, P.K., Wantland, D.J., Moezzi, S. and Willard, S. (2009) Exploring HIV stigma and quality of life for persons living with HIV infection. Journal of the Association of Nurses in AIDS Care, 20(3), pp.161-168.
Katz IT, Ryu AE, Onuegbu AG, Psaros C, Weiser SD, Bangsberg DR et al. Impact of HIV-related stigma on treatment adherence: systematic review and meta-synthesis. J Int AIDS Soc. 2013;16(Suppl 2): 18640. Available from: http://www.jiasociety.org/index.php/ jias/article/view/18640 Accessed March 21, 2021
Kemenkes RI 2019. Laporan Nasional Riskesdas 2018.
Link, B.G. and Phelan, J.C. (2001) Conceptualizing stigma. Annual review of Sociology, pp.363-385.
UNAIDS. (2005) HIV-Related Stigma, Discrimination and HUman Rights Violations: Case studies of successful programmes, viewed 10 April 2021,. (https://data.unaids.org/publications/irc-pub06/jc999-humrightsviol_en.pdf)
UNAIDS. (2018) Global partnership for action to eliminate all forms of HIV-related stigma and discrimination, viewed 10 April 2021,. (https://www.unaids.org/en/resources/documents/2018/global-partnership-hiv-stigma-discrimination)
World Health Organization 2020, HIV/AIDS – Transmission, World Health Organization, viewed 1 April 2021 (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids)
Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya.