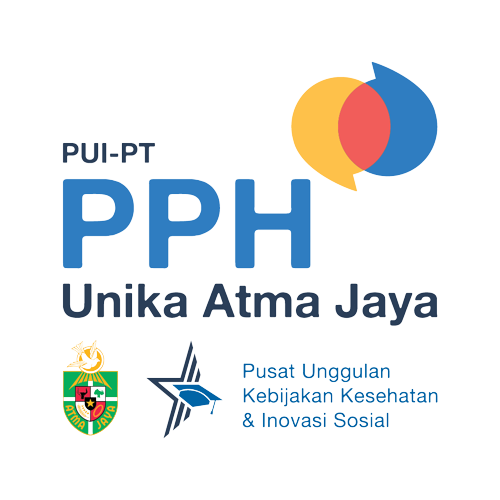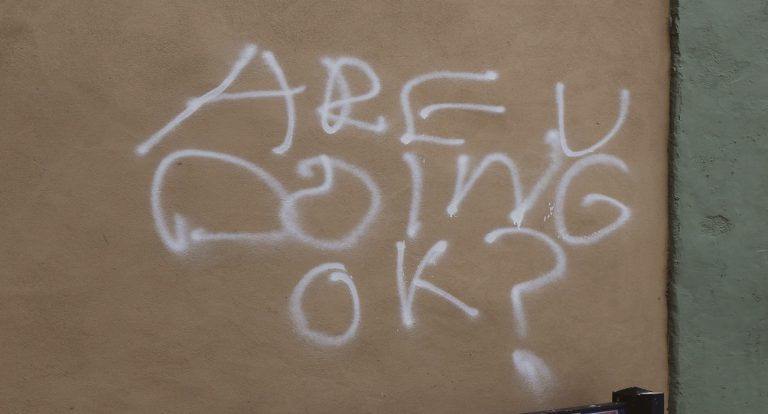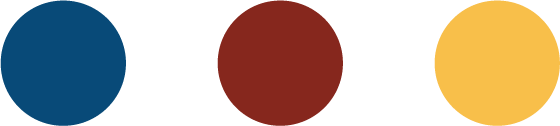Situasi satu tahun belakangan ini sepertinya mendorong banyak dari kita ke titik terendah. Mulai dari pandemi, ketakutan diri atau orang tersayang tertular Covid-19, keharusan untuk berdiam diri di rumah untuk waktu lama, keterbatasan berinteraksi dengan orang lain, ketidakstabilan kondisi keuangan, bahkan sampai berita kematian orang terdekat. Saya pikir adil jika menyimpulkan, kita dipaksa untuk hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian, menyerah dan melepaskan segala rutinitas yang biasa kita jalani selama bertahun-tahun sebelum pandemi, berdiam diri, dan akhirnya terjebak dengan pikiran kita sendiri. Tentunya hal ini tidak menyenangkan. Bagi saya, pikiran telah menjadi musuh yang mendorong diri ke dalam lubang gelap.
Sejak awal 2020, sampai sekarang, saya mengalami kesulitan tidur yang cukup mengganggu. Hampir setiap hari saya terjaga di tempat tidur, sepanjang malam, dengan pikiran yang tidak menentu, memikirkan berbagai hal yang sebetulnya mungkin tidak perlu dipikirkan. Setiap harinya saya hanya akan tidur selama tiga sampai empat jam, lebih sedikit dari yang dibutuhkan oleh orang-orang seusia saya. Bukannya saya tidak melakukan apapun untuk mengatasi masalah ini, menciptakan suasana tidur yang nyaman, berusaha untuk tenang, menjauhkan diri dari gadget, tidak mengonsumsi kafeina, olahraga secara rutin, membaca, menggunakan aromaterapi, sampai bermeditasi. Rasanya semua cara yang bisa ditemukan di internet, telah dicoba. Bahkan seorang teman mengirimkan produk herbal yang bisa membantu tidur. Saya hargai niat baiknya, tapi produk tersebut masih belum mampu membuat saya tertidur pulas.
Jenuh dengan situasi ini, saya memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Jika dibiarkan, kesulitan tidur dan beberapa keluhan lainnya yang saya rasakan mulai mengganggu kesehatan fisik, psikologis, dan emosional. Setelah menghabiskan waktu untuk mengeksplorasi kemungkinan tenaga profesional yang tepat, entah itu psikolog, psikiater, dokter, dan sebagainya, akhirnya pilihan saya jatuh kepada sebuah aplikasi telemedis yang menawarkan jasa konsultasi jarak jauh antara pasien dan tenaga kesehatan. Alasan saya memilih layanan telemedis sebenarnya sangat sederhana, saya berpikir bisa mendapatkan bantuan profesional tanpa perlu harus repot pergi ke klinik atau rumah sakit. Tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan di situasi pandemi, di mana kita memang harus membatasi aktivitas di luar rumah dan menjaga jarak, selain itu harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau.
Setelah memantapkan niat, akhirnya saya mengakses layanan tersebut. Saya dihubungkan dengan salah seorang tenaga kesehatan profesional. Perlu diingat bahwa rating beliau sangat tinggi, artinya banyak orang yang puas menggunakan jasa beliau. Konsultasi dilakukan secara online, melalui bantuan chat, dan dibatasi selama 30 menit. Pembicaraan diawali dengan perkenalan diri, lalu beliau menanyakan keluhan yang saya rasakan. Saya mencoba menceritakan segala keluhan dengan sedetil mungkin. Kemudian obrolan dilanjutkan dengan pertanyaan lainnya. Sebagai lulusan fakultas psikologi, pertanyaan yang diajukan rasanya cukup familier. Lama-kelamaan, rangkaian pertanyaan semakin mirip dengan daftar gejala salah satu gangguan psikologis yang tertera pada DSM-V[1]. Satu pertanyaan, dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, begitu seterusnya selama hampir 20 menit, beliau bertanya dan saya menjawab. Mendekati menit ke-30, beliau akhirnya mulai menyimpulkan mengenai kemungkinan gangguan yang saya derita, dan mengakhiri konsultasi dengan kesimpulan bahwa saya harus mengakses layanan kesehatan di rumah sakit.
Sesudah konsultasi selesai, saya berdiam sejenak, menanyakan kepada diri apa yang baru saja saya lakukan, dan mencoba merefleksikan pengalaman saya melalui beberapa pertanyaan.
Bagaimana perasaan saya selama sesi konsultasi? Sejujurnya, teramat lelah. Saya merasa pembicaraan berlangsung lebih dari 30 menit, walaupun kenyataannya kurang. Saya seperti sedang mengisi formulir asesmen, menjawab pertanyaan demi pertanyaan, sambil menerka-nerka pertanyaan yang akan diajukan berikutnya. Bukannya merasa keberatan dengan kemungkinan diagnosa yang akan diberikan, tetapi pertanyaan yang diajukan sangat textbook, persis seperti yang saya pelajari selama kuliah.
Bagaimana perasaan saya setelah selesai konsultasi? Saya merasa bingung, tidak mendapatkan kejelasan tentang apa yang terjadi atau apa yang menjadi masalah saya, hanya kemungkinan diagnosa yang diberikan setelah menjawab serangkaian pertanyaan, serta anjuran untuk mengunjungi tenaga profesional. Konsultasi selesai tanpa resep, saran terapi, atau informasi mengenai rujukan rumah sakit yang bisa diakses. Hanya pernyataan bahwa saya memiliki ‘masalah’ dan membutuhkan bantuan profesional. Tentu saja saya bisa memahami bahwa proses pemberian layanan kesehatan jiwa tidak instan. Ada beberapa langkah yang harus dilewati, sampai diagnosa berhasil ditegakan dan pengobatan atau terapi bisa dilakukan.
Lalu, sebenarnya apa yang saya harapkan dari sesi konsultasi? Saya berharap agar situasi dan perasaan saya dapat dipahami, tidak didefinisi oleh serangkaian pertanyaan, lalu disimpulkan seperti hasil survei. Yang terpenting, saya berharap ada sedikit empati[2] dalam konsultasi. Empati, sebuah konsep yang amat digaungkan ketika membahas kesehatan jiwa. Sayangnya pada kesempatan kali ini, saya tidak merasakannya.
Kenyataannya, pergeseran bentuk layanan kesehatan dari layanan konvensional menjadi daring telah berlangsung cukup lama. Banyak aplikasi atau lembaga yang sudah berinovasi dan mulai menerapkan bentuk pelayanan telemedis. Perrin, Pierce, dan Elliot (2020) menyatakan bahwa pandemi memang mendorong terjadinya ‘revolusi telemedis’. Bagaimana tidak, tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan dipaksa untuk mengalihkan pelayanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan jiwa ke alternatif yang bisa meminimalisir penyebaran Covid-19. Penggunaan teknologi untuk menyelenggarakan layanan kesehatan jarak jauh menjadi solusi untuk mengatasi pembatasan sosial yang diterapkan oleh pemerintah, serta dapat menjangkau pasien yang tidak dapat mengunjungi fasilitas kesehatan. Dengan segala kemudahannya, baik dari segi kepraktisan, efisiensi, biaya, sampai kemanjurannya, layanan telemedis telah menjadi primadona.
Tentunya ada pula beberapa isu yang harus dipertimbangkan ketika kita membicarakan layanan telemedis. Salah satunya, tidak semua jenis gangguan psikologis memang dapat didiagnosa dan mendapatkan pengobatan atau terapi via daring. Belum lagi isu kerahasiaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Selain itu, saya sendiri juga tertarik dengan bagaimana relasi terapeutik antara tenaga profesional dan pasien dapat terbentuk melalui konsultasi telemedis, bagaimana cara menyampaikan empati melalui daring?
Saya meyakini banyak orang lain yang cocok menggunakan layanan telemedis untuk mendapatkan bantuan kesehatan profesional, apalagi pada situasi sekarang. Tetapi, pengalaman mengakses layanan telemedis membuat saya sedikit skeptis. Mungkin memang saya yang kuno dan tidak terbiasa dengan layanan canggih, sehingga belum puas rasanya jika tidak langsung menceritakan keluh kesah di hadapan manusia lainnya. Saya yakin, akan ada peluang lainnya bagi saya untuk menggunakan layanan telemedis di masa mendatang, dan tentu saja saya akan mencoba. Bisa saja pengalaman berikutnya akan berbeda, bukan?
Catatan: Tulisan ini merupakan refleksi atas pengalaman pribadi penulis, tidak bertujuan menyinggung layanan kesehatan atau jenis profesi tertentu.
Referensi
Perrin, P. B., Pierce, B. S., & Elliott, T. R. (2020). COVID ‐19 and telemedicine: A revolution in healthcare delivery is at hand. Health Science Reports, 3(2). Doi: https://doi.org/10.1002/hsr2.166
Pierce, B. S., Perrin, P. B., Tyler, C. M., McKee, G. B., & Watson, J. D. (2021). The COVID-19 telepsychology revolution: A national study of pandemic-based changes in U.S. mental health care delivery. American Psychologist, 76(1), 14-25. Doi: https://doi.org/10.1037/amp0000722
[1] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Edisi 5 (DSM-V) adalah buku panduan diagnosa gangguan psikologis yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA)
[2] Empati adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, serta turut merasakan emosi atau perasaan orang lain.
Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya.