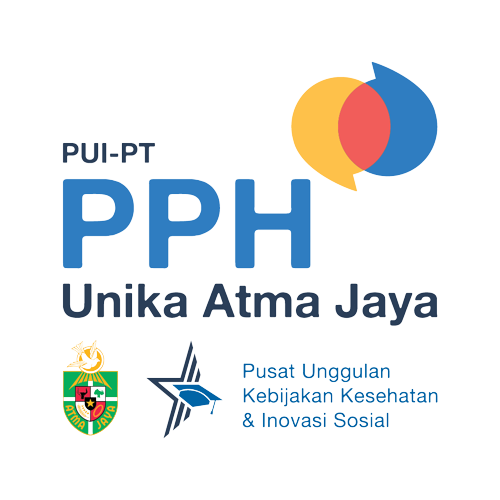Bila ku mati
Kau juga mati
Walau tak ada cinta, sehidup semati”
Familier dengan penggalan lirik lagu di atas? Atau mungkin, sebagian dari kamu diam-diam terbawa suasana dan jadi bersenandung? Atau bisa jadi, ingatanmu kembali pada tahun 2000an awal ketika video musik lagu “Posesif” milik Naif ini sukses merajai saluran musik lokal di televisi. Kala itu, booming lagu Posesif beriringan dengan meroketnya nama Jeanny Stavia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Avia tau Avi “Naif”, si pemeran utama dalam video musik Posesif. Di industri hiburan, Jeanny Stavia bukan nama asing, sebelum muncul di video musik Posesif, ia pernah meraih predikat “Ratu Waria Indonesia” pada tahun 1997, tergabung dalam grup Golden Boys, dan jadi langganan tampil sebagai bintang tamu dalam acara komedi serta reality show. Sosok Avi yang sempat mencuri perhatian, dan kualitas lagu milik Naif yang saat itu juga sedang naik daun seharusnya bisa jadi representasi positif bagi teman-teman Transgender. Namun sayangnya, sebagian orang malah menginterpretasikan lagu Posesif dan video musiknya secara berbeda. Perpaduan lirik “Bila ku mati, kau juga mati” dan identitas Avi sebagai transgender dalam video musiknya justru kerap jadi pembenaran stigma.
“Ada yang bilang, transgender itu versi lebih parah dari gay, dibuat-buat, harus bertobat, menyeramkan, sadis. Tuh, sadis. Kan ‘bila ku mati kau juga mati’?”, kelakar Kevin Halim, seorang Transgender & LGBT Rights Activist di tengah-tengah ruang perkuliah Gedung C Lt.8 Kampus UNIKA Atma Jaya Semanggi pada Rabu siang 4 September 2019 lalu. Kehadiran Kevin Halim di UNIKA Atma Jaya bukan tanpa sebab. Kevin yang juga alumnus Fakultas Psikologi UNIKA Atma Jaya tengah mengisi materi salah satu kegiatan rutin Pusat Penelitian HIV AIDS UNIKA Atma Jaya (PPH UAJ), Lecture Series. Kali ini temanya adalah “[De]Psikopatologisasi Sebagai Upaya Mengurangi Stigma dan Diskriminasi Terhadap Transgender”.
Psikopatologi dan [De]Psikopatologisasi
Apa yang sebenarnya dimaksud dengan psikopatologi? Sederhananya, psikopatologi merupakan cabang ilmu yang menelaah tentang gangguan jiwa. Dalam psikopatologi, para ahli mendefinisikan gangguan mental yang mungkin dialami seseorang. Gangguan mental yang dialami seseorang dapat menyebabkan ia mengalami penurunan kualitas hidup. Pasalnya, orang tersebut akan merasakan penderitaan di dalam diri, ketidakmampuan melakukan sejumlah aktivitas penting dalam berkehidupan, hingga banyaknya perilaku atau sikap-sikap yang kerap dikategorikan sebagai pelanggaran normal sosial serius di tengah masyarakat. Sementara itu, yang dimaksud dengan depsikopatologisasi adalah upaya untuk membuat suatu diagnosis gangguan -yang dianggap sebagai penyakit mental- menjadi netral atau bukan gangguan penyakit mental.
Pada kelompok transgender, tidak dapat dipungkiri bahwa perlakuan stigma dan diskriminasi yang terjadi juga dikarenakan klasifikasi psikopatologi yang memasukan transgender sebagai gangguan mental. Sehubungan dengan hal ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia bahkan sempat mengelompokan transgender sebagai “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”. Pengelompokan ini tentu saja segera menimbulkan pertanyaan dan keresahan. Sebab, banyak kelompok transgender yang masih dapat melakukan aktivitas sosialnya dengan baik dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya secara mumpuni.
“Mengenal psikopatologi itu penting sekali, kenapa? Karena banyak kesalahpahaman di masyarakat tentang suatu penyakit mental, akhirnya jadi salah persepsi dan membuat penanganan terhadap seseorang yang diduga memiliki permasalahan atau gangguan mental jadi salah juga. Kesalahanpahaman yang terjadi ketika orang tidak tahu psikopatologi juga menghasilkan stigma di masyarakat untuk kelompok tertentu, misalnya transgender yang sering sekali dipsikopatologisasikan. Selain itu dengan mengenal psikopatologi kita juga bisa mengenal sejarah psikopatologi di Indonesia dan akhirnya membantu melihat perkembangan kita sekarang”, terang Kevin.
Menyambung penjelasan Kevin terkait psikopatologi dan stigma yang membayangi transgender, peserta yang turut hadir pada acara Lecture Series “[De]Psikopatologisasi Sebagai Upaya Mengurangi Stigma dan Diskriminasi Terhadap Transgender” pun angkat bicara. Salah seorang transpuan -transgender perempuan- berinisial A berbagi pengalaman penerimaan keluarga terkait identitas gendernya.
Beberapa tahun lalu, A yang telah membuka identitasnya sebagai transgender kepada keluarganya, memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta. Perjalanannya di Ibukota membawa angin segar, ia bekerja di rumah mode salah satu desainer ternama di Indonesia dan membekali dirinya dengan pengetahuan terkait HIV/AIDS dan IMS -Infeksi Menular Seksual-. Sembari tersenyum penuh percaya diri, A mengatakan, “Aku merasa aku lebih bisa diterima saat membuktikan bahwa aku, transgender, bisa memiliki profesi lain selain pengamen dan pekerja seks. Aku bekerja di tempat desainer, lalu aku juga ikut organisasi teman-teman waria, sosialisasi, belajar tentang HIV/AIDS dan IMS. Jadi aku justru sering berbagi pengetahuanku juga ke keluargaku dan mereka jadi lebih bisa menerima aku.”
Psikolog Klinis Harus Menghindari Sifat Asumtif dan Bias
Materi kedua Lecture Series “Depsikopatologisasi Sebagai Upaya Mengurangi Stigma dan Diskriminasi Terhadap Transgender” disampaikan oleh Anastasia Satriyo, M.Psi dan Gisella Tani Pratiwi, M.Psi. Keduanya adalah Psikolog Klinis. Mereka membawakan materi tentang “Peranan Helping Professions Dalam Membantu Kesehatan Mental Pada Kelompok Transgender”. Membuka pembahasan, Anastasia menceritakan jika dibandingkan dengan populasi umum, transgender cenderung memiliki pengalaman yang lebih tinggi terhadap beberapa permasalahan kesehatan. Diantaranya adalah infeksi HIV, penyalahgunaan obat-obatan, permasalahan kesehatan mental, kekerasan, dan viktimisasi. Untuk menguraikan dan mengurangi beban permasalahan yang dihadapi oleh transgender diperlukan bantuan dari berbagai pihak dan salah satu yang dapat berperan adalah Psikolog Klinis.
“Psikolog Klinis bisa membantu, caranya adalah dengan selalu mengedepankan prinsip layanan psikologis yakni penghormatan pada hak dan martabat individu, kompetensi, tanggungjawab, integritas, non-diskriminatif, memberdayakan dan kesetaraan, sehingga atas dasar itu seorang psikolog semestinya tidak membeda-bedakan siapa pasiennya. Perempuan, laki-laki, trangender, LGBT, siapa pun dia harus dipandang sama”, ucap Anastasia.
Gisella Tani Pratiwi, M.Psi kemudian menambahkan, “Psikolog juga jangan asumtif dan bias. Bias dapat menyebabkan seorang psikolog memutuskan sesuatu berdasarkan penilaian pribadi yang subjektif dan cenderung memberi stigma negatif. Bias ini membuat pusatnya adalah penilaian “saya”, dan bukannya berempati pada klien. Bias ini tentu saja memberi dampak, seperti memperburuk kesehatan mental klien, klien merasa tersudutkan dan dipersalahkan, hingga dapat menurunkan kesempatan klien untuk mengembangkan dirinya.”
Bagi PPH UAJ sendiri, mendiskusikan depsikopatologisasi terhadap transgender secara ilmiah merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Isu ini menjadi sangat penting bukan hanya karena menyangkut pemenuhan hak bagi setiap warga negara seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga karena berdampak negatif pada masalah kesehatan -mental, fisik, dsb-, sosial dan ekonomi. Tidak adil rasanya bila seseorang atau sekelompok orang terus menerus dirundung stigma dan diskriminasi yang salah satunya juga disebabkan oleh pembenaran keliru mengenai psikopatologisasi. Oleh karena itu, depsikopatologisasi merupakan salah satu jalan yang mesti ditempuh untuk mengurai permasalahan psikopatologisasi terhadap teman-teman transgender.