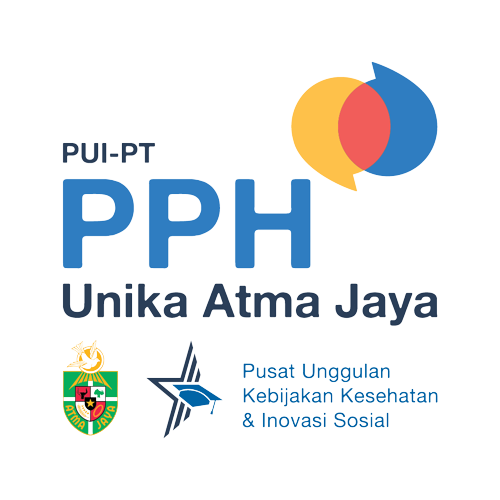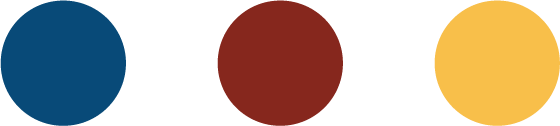Apa yang terbesit di benak kita saat mendengar penderita gangguan mental? Mungkin sebagian dari kita membayangkan sosok yang menggelandang tanpa busana atau termakan bentukan budaya populer yang kerap menampilkan sosok psikopat yang haus darah dan gemar menyiksa. Namun, jika kita mengintip DSM 5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) milik mahasiswa psikologi, apa yang dikatakan sebagai gangguan mental spektrumnya sangat luas. Terdapat berbagai gangguan mental dengan kategori tingkat keparahan ringan hingga berat. Beberapa dari kita mungkin sudah tidak asing dengan gangguan insomnia, kecemasan, stres, psikosomatis dan depresi, tapi yang menjadi refleksi kita bersama, sejauh mana ketersediaan jaring perawatan yang aksesibel dan aman bagi penderita gangguan mental emosional?
Sulitnya menjaring kasus gangguan mental emosional
Pemerintah menerjemahkan masalah kejiwaan berat dengan istilah gangguan jiwa sedangkan untuk kasus yang lebih ringan digunakan istilah gangguan mental emosional. Bisa dikatakan sejauh ini pemahaman masalah kejiwaan di Indonesia masih didominasi dengan gangguan jiwa berat. Meskipun UU Keswa no. 18/2014 sudah mengakui keberadaan gangguan mental emosional dengan istilah ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan), namun peraturan turunan yang dapat menjangkau penemuan kasus gangguan mental emosional masih relatif lemah. Hal ini terefleksi dalam berbagai dukungan kebijakan yang begitu fasih berbicara mengenai penemuan kasus dan penanganan gangguan jiwa berat, diantaranya Permenkes no 54/2017 tentang penanggulangan pemasungan orang dengan gangguan jiwa, Permenkes no 4/2019 tentang SPM bidang Kesehatan yang mencakup amanah 100% ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) berat tertangani serta Permenkes no. 39/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK (Program Indonesia Sehat- Pendekatan Keluarga) turut memasukkan penanganan pada ODGJ berat. Berbagai dukungan kebijakan tersebut menimbulkan adanya kesenjangan perawatan (treatment gap) terutama bagi penderita gangguan mental emosional. Temuan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mengafirmasi hal tersebut bahwa dari hampir 12 juta orang penderita depresi hanya 9% atau sekitar 1 juta orang penderita depresi yang memperoleh pengobatan.
Berbeda dengan kasus gangguan jiwa berat yang dapat dengan mudah diidentifikasi karena cenderung memiliki gejala gaduh gelisah dan terputus dari realitas, gejala gangguan mental emosional cenderung lebih subtil karena umumnya penderita masih bisa berinteraksi dan berfungsi secara sosial. Dengan karakter gejala yang bersifat laten ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam penemuan kasus dan penanganan gangguan mental emosional. Sejauh ini penemuan kasus gangguan mental emosional mengandalkan sensitivitas/kepekaan dari dokter yang bertugas di layanan umum maupun kesadaran dari individu terkait masalah kesehatan mental yang dialami.
Peliknya penemuan kasus gangguan mental emosional dimotori oleh absennya agenda kebijakan yang memberi perhatian pada gangguan mental emosional dan diperburuk dengan persoalan kultural. Dalam hal ini persoalan kultural seperti stigma dan sempitnya pemahaman masalah kejiwaan menjadi batu sandungan dalam pemanfaatan layanan keswa. Seberapa sering kita menjumpai cerita tentang keinginan mengakhiri hidup dimentahkan dengan gagasan kurang iman atau kurang bersyukur? Tak jarang pula, penderita gejala gangguan mental emosional enggan untuk mengakses layanan keswa karena khawatir akan dilabeli ‘gila’ oleh lingkungan sekitarnya. Setelah mengakses layanan keswa pun mereka tak pelak dihinggapi kecemasan dan harus menutupi kondisi mentalnya dari keluarga, kerabat, lingkungan kerja karena dirasa dapat membawa aib.
Mendorong perawatan bagi penderita gangguan mental emosional
Berangkat dari perbedaan gejala antara gangguan jiwa dan gangguan mental emosional tentu memerlukan pendekatan yang berbeda dalam menjaring kasus gangguan mental emosional. Jika inisiasi penemuan kasus pada gangguan jiwa berat biasanya datang dari pihak eksternal seperti keluarga; tenaga kesehatan atau masyarakat sekitar, penemuan kasus gangguan mental emosional justru membutuhkan inisiasi dari individu yang bersangkutan. Mengingat kunci dari penemuan kasus bertumpu pada kesadaran individu maka perlu kegiatan sosialisasi maupun edukasi terkait gangguan mental emosional di lingkungan sekolah, kantor, keluarga. Memutus stigma juga harus menjadi agenda prioritas dalam kegiatan sosialisasi sehingga dapat mengurai keenganan masyarakat untuk mengakses layanan keswa. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan pun perlu dibekali dengan perluasan pemahaman mengenai gejala-gejala dari gangguan mental emosional dan kapasitas untuk melakukan skrining kejiwaan. Pada beberapa kasus dibutuhkan kepekaan dokter di layanan umum untuk mengidentifikasi adanya masalah mental yang dapat ditelusuri dari keluhan pasien yang berulang dan tidak menunjukkan perubahan apapun setelah mendapat terapi obat.
Mengurai kemacetan akses dan sumber daya dalam perawatan penderita gangguan mental emosional memang terbilang cukup kompleks. Namun, titik berangkatnya dapat disiasati dengan penguatan struktural berupa peraturan turunan yang lebih memusatkan penemuan kasus dan penanganan bagi gangguan mental emosional. Dengan demikian, perawatan masalah kejiwaan tidak lagi timpang pada pemenuhan SPM kesehatan yang menargetkan 100% ODGJ berat tertangani tapi diharapkan layanan keswa dapat melakukan penanganan masalah kejiwaan secara menyeluruh di masa yang akan datang.
Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya.