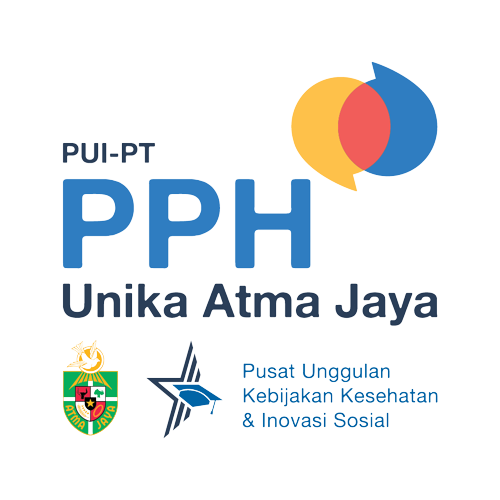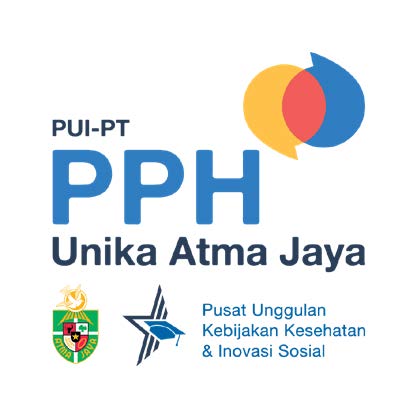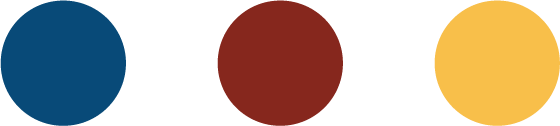“Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita siapkan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dalam kandungan sampai tumbuh mandiri, juga meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya”.
Pidato Presiden Republik Indonesia ke- 7, Jokowi dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 16 Agustus 2018.
Dalam RPJMN 2020-2024 indikator capaian pembangunan terkait pemenuhan layanan dasar cenderung terpusat pada penyakit menular (HIV/AIDS, TB, dan malaria), stunting pada balita, kesehatan reproduksi, penyakit tidak menular seperti obesitas, tekanan darah tinggi, stroke, jantung, serta diabetes. Hal serupa juga terlihat pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang mencanangkan upaya kesehatan pada: kesehatan reproduksi, kesehatan bayi, gizi masyarakat, penyakit tidak menular (seperti tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak; perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol), dan penyakit menular (seperti HIV/AIDS dan malaria) (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Dengan kata lain, belum ada perhatian nyata terhadap kesehatan jiwa dari skema kesehatan nasional. Berkaca pada definisi kesehatan menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera pada aspek fisik, mental, dan sosial, serta bukan sekedar absennya penyakit (WHO, 1946).
Absennya keswa pada skema kesehatan nasional Indonesia bukan berarti permasalahan keswa dapat dianggap remeh. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2018 menunjukkan dari jumlah 194,779,441 penduduk berusia 15 tahun atau lebih di Indonesia, diperkirakan terdapat sekitar 19 juta orang kelompok umur tersebut yang mengalami gangguan mental emosional, dan hampir 12 juta mengalami depresi. Sayangnya, tingginya prevalensi tersebut tidak diikuti tingkat cakupan pengobatan. Dari sekitar 12 juta penderita depresi, hanya 9% atau sekitar 1 juta orang yang menjalani pengobatan (Kemenkes, 2018). Tidak hanya gangguan depresi, terdapat prevalensi gangguan psikosis atau skizofrenia sebanyak 7 per 1,000 rumah tangga (Kemenkes, 2018). Pemasungan kerap dianggap sebagai solusi pragmatis dan manifestasi frustasi bagi keluarga yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan jiwa (Laila, Mahkota, Krianto, & Shivalli, 2018). Tentunya pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan ini semestinya menjadi tanggung jawab negara terhadap warganya.
Kebijakan Kesehatan Jiwa yang Ala Kadarnya
Sayangnya, permasalahan dan kesenjangan yang ada masih belum ditanggapi secara responsif oleh pemerintah. Diantaranya tercermin mulai dari urusan keswa yang masih digabungkan dengan urusan NAPZA, yakni dalam Sub Direktorat Kesehatan Jiwa dan Napza. Tidak hanya itu, kebijakan yang tersedia pun juga masih ala kadarnya. Undang-undang keswa yang sudah terbit sejak 2014 masih belum memiliki kebijakan turunan (UU No. 18 Tahun 2014). Nihilnya kebijakan turunan membuat UU tersebut tidak terkontekstualisasikan secara nyata dalam pemberian layanan keswa di lapangan, khususnya puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer.
Salah satu masalah yang cukup besar adalah belum adanya standar regulasi yang mengatur tenaga pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat. Akibatnya tidak semua puskesmas memiliki layanan kesehatan jiwa karena tidak memikiki tenaga kesehatan yang kompeten di bidang itu. Akhirnya, terdapat beberapa Dinas Kesehatan kota tertentu yang berinisiatif untuk menyediakan psikolog ataupun psikiater bagi puskesmas, yakni dengan kolaborasi bersama perguruan tinggi (Negara, Langi, Kurniawan, Devika, Abdurahman, & Praptoraharjo, 2020). Tindakan ini tentunya tidak perlu dilakukan seandainya sudah ada kebijakan maupun standar jelas yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan jiwa di puskesmas.
SDM Ala Kadarnya
Salah satu penyebab ketimpangan antara tingginya prevalensi masalah keswa dan tingkat pengobatan, ada pada aspek SDM tenaga keswa. Pada tahun 2018 tercatat jumlah psikiater di Indonesia ialah sekitar 773 orang, dengan catatan bahwa 70% diantaranya bekerja di Pulau Jawa. Dengan kata lain, jika rasio jumlah penduduk Indonesia adalah 250 juta orang, maka seorang psikiater harus mampu melayani 323,000 orang (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018). Ketersediaan psikiater ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan WHO, yakni 1: 30,000 orang (data menurut dr. Fidiansyah dalam Pols dkk. (2019).
Tidak sebatas ketersediaan. Kualitas atau kapasitas tenaga kesehatan yang saat ini sudah bekerja di puskesmas pun juga masih terbatas. Di sisi lain, kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas masih kerap terbatas karena adanya batasan kuota nakes yang dapat diikutsertakan, sehingga membuat para nakes harus bergiliran untuk dapat mengikutinya (Negara, Langi, Kurniawan, Devika, Abdurahman, & Praptoraharjo, 2020).
Relevankah membangun SDM unggul tanpa memperhatikan kesehatan jiwa?
Upaya penangan permasalahan kesehatan jiwa yang ala kadarnya tentu tidak sesuai dengan upaya kesehatan yang bertujuan untuk mencapai status kesehatan yang setinggi-tinggi baik secara fisik, mental, dan kesejahteran sosialnya. Membiarkan penyelesaian masalah kesehatan pada pelayanan kesehatan yang tidak terstandar tentu tidak menjamin kualitas pelayanan yang diharapkan bisa mendukung terbangunnya SDM unggul di masa depan. Jika negara memang sudah menetapkan “SDM unggul” sebagai program pembangunan, kiranya itu tidak sekedar menjadi slogan programatik belaka.
Rujukan:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2015 – 2019 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
Laila, N.H., Mahkota, R., Krianto, T., & Shivalli, S. (2018). Perceptions about pasung (physical restraint and confinement) of schizophrenia patients: a qualitative study among family members and other key stakeholders in Bogor Regency, West Java Province, Indonesia 2017. International journal of mental health systems, 12(1), p.35.
Negara, M.D., Langi, G.G., Kurniawan, H., Devika, Abdurahman, I., & Praptoraharjo, I. (2020). Evaluasi implementasi kebijakan layanan kesehatan jiwa di puskesmas. Belum dipublikasikan. Jakarta: Pusat Penelitian HIV AIDS Unika Atma Jaya
Pols, H., Setiawan, P., Marchira, C. R., Suci, E. S. T., Good, M. J. D, & Good, B. J. (2019). Jiwa sehat, negara kuat: Masa depan layanan kesehatan jiwa di Indonesia (Vol. 2). Jakarta: Penerbit Buku Kompas
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
World Health Organization. Preamble of the constitution of the World Health Organization. International Health Conference, New York, 19 June – 22 July 1946, p. 983-984.
Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya.