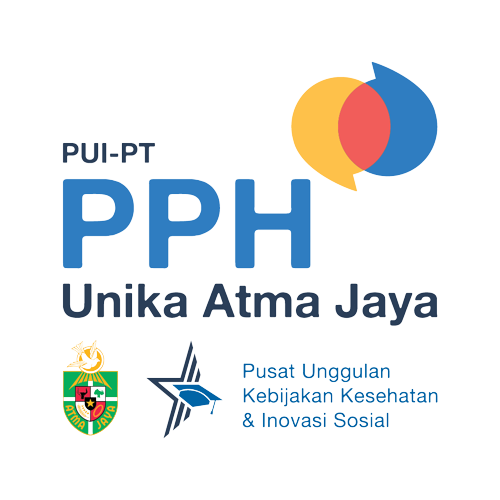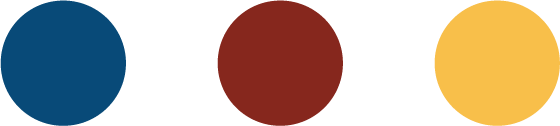Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 membuat kita semua dituntut mengikuti berbagai imbauan atau aturan kesehatan. Salah satunya dengan sebisa mungkin untuk berada di rumah dan melakukan aktivitas dari sana. Tentunya hal ini dimaksudkan dengan niat baik, yakni mengurangi kuantitas penularan virus COVID-19. Dalam imbauan tersebut sering pula disertai nasehat agar memanfaatkan momen ini untuk mengakrabkan diri dengan keluarga atau kerabat di rumah.
Pada kenyataannya, tidak semua individu memiliki rumah “ideal” berisikan orang-orang dengan keyakinan, nilai, atau prinsip yang sejalan dengan individu tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bahwa mulanya seseorang memutuskan untuk pindah rumah akibat perbedaan itu. Salah satu bagian kelompok masyarakat yang rentan mengalami isu ini adalah mereka yang memiliki keragaman ekspresi gender dan/atau orientasi seksual, seperti LBGTQ. Saya sendiri baru menyadari keberadaan isu ini setelah berselancar daring dan membaca beberapa artikel berita internasional, misalnya saja BBC News, khususnya pada laman topik kesehatan mental.
Beberapa artikel menceritakan bagaimana tantangan dan beban mental yang harus diemban para penulis ataupun narasumber yang memiliki keberagaman seksual akibat pandemi ini (Hunte, 2020; Irungu & Zoric, 2020). Terutama karena mereka kehilangan pekerjaan, sehingga memaksa mereka diam atau menetap di rumah. Lalu, ada pula yang sampai harus pindah ke rumah sanak keluarga atau kerabatnya, akibat tidak bisa menanggung biaya tempat tinggal. Namun sayangnya, sanak keluarga atau kerabat menolak status para penulis/narasumber sebagai LGBTQ. Salah satu artikel menceritakan bagaimana seorang narasumber “diasingkan” oleh orang-orang rumahnya (Hunte, 2020). Ia (narasumber) tidak diperbolehkan mengonsumsi makanan yang dibeli oleh ibu dan pasangan ibunya, selain itu pasangan ibunya kerap mengatakan hal buruk terkait narasumber di hadapan narasumber sendiri. Padahal sebelum pandemi, ia dengan sengaja mengatur jadwal aktivitasnya supaya lebih banyak dihabiskan di luar rumah.
Membaca ragam artikel bertema kesehatan mental pada LGBTQ di tengah pandemi COVID-19 membuat saya berefleksi, bahwa kata sifat aman yang seringkali diasosiasikan dengan rumah belum tentu bisa dirasakan oleh semua kalangan. Pesan untuk mendekatkan diri dengan keluarga di rumah pun rasanya malah dapat menambah perasaan tidak berdaya bagi sebagian orang. Terlebih bagi mereka yang ditolak oleh orang serumahnya karena memiliki orientasi seksualnya yang dinilai “berbeda”.
Seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 mengancam kesehatan fisik, hal Ini membuat aturan dan imbauan yang banyak disosialisasikan pun juga lebih menekankan pada aspek fisik. Akan tetapi, ada kenyataannya, aspek mental juga merupakan bagian dari diri manusia sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh World Health Organization atau WHO (1946, Juli), bahwa yang dimaksud dengan kesehatan ialah terdiri kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial, serta bukan sekedar berfokus pada ketiadaan penyakit.
Dari definisi tersebut di atas, diketahui bahwa kondisi fisik hanya merupakan salah satu aspek dalam kesehatan karena ia turut diiringi dengan masalah kesehatan mental dan kesejahteraan sosial. Pada situasi pandemi ini, telah ada pula berbagai publikasi lain yang menunjukkan pengaruh kebijakan berupa lockdown, social distancing, physical distancing ataupun kebijakan dengan sebutan lain yang menuntut warganya untuk menetap di rumah (tergantung kebijakan negara yang menjadi lokasi) berindikasi memberikan dampak negatif pada kesehatan mental kelompok LGBTQ. Ini tercermin pada temuan beberapa publikasi baik berupa studi penelitian atau artikel himbauan.
Salah satu studi menunjukkan bahwa kelompok imigran LGBTQ lebih rentan menghadapi masalah kesehatan dan masalah sosial akibat potensi lingkungan rumah yang tidak stabil (Kline, 2020). Kemudian dalam artikel yang disusun oleh Lee dan Miller (2020) menampilkan bahwa kelompok LGBTQ (khususnya yang lansia) lebih rentan terkena dampak negatif dari isolasi sosial akibat adanya potensi ditolak oleh keluarga atau teman dekat akibat status LGBTQ mereka. Hal-hal di atas mengindikasikan bahwa strategi menghadapi pandemi COVID-19 tidak bisa hanya sekedar berfokus pada aspek kesehatan fisik. Strategi yang disusun pun tidak bisa dipukul rata bisa efektif bagi semua kalangan masyarakat. Perlu ada strategi solutif yang lebih spesifik sesuai dengan karakterstik tertentu, sehingga tidak terjadi ketimpangan bagi mereka yang tergolong minoritas.
Disclaimer: Tulisan ini mewakili opini penulis dan tidak menggambarkan opini dan sikap Pusat Penelitian HIV Atma Jaya.
Referensi:
Browne, K., Banerjea, N., & Bakshi, L. (2020). Survival and liveablity in #COVIDtimes: Queer women’s transnational witnessing of COVID-19. Dialogue in Human Geography, XX(X), 1-4. doi: 10.1177/2043820620930833
Hunte, B., (2020, Maret 26). Coronavirus: I’m stuck in isolation with my homophobic parents’. BBC News. Diakses dari https://www.bbc.co.uk/news/amp/uk-52039832
Irungu, A., & Zoric, M. (2020, Mei 31). LGBT: COVID-19 forced me back home where I’m ‘unwanted’. BBC News. Diakses dari https://www.bbc.com/news/av/world-africa-52835114/lgbt-covid-19-forced-me-back-home-where-i-m-unwanted
Kline, N. S. (2020). Rethinking COVID-19 vulnerability: A call for LGBTQ+ im/migrant health equity in the United States during and after a pandemic. Health Equity, 4(1), 239-242. doi: 10.1089/heq.2020.0012
Lee, H., & Miller, V. J. (2020). The disproportionate impact of COVID-19 on minority groups: A social justice concern. Journal of Gerontological Social Work, 1-5. doi: 10.1080/01634372.2020.1777241
World Health Organization. (1946, Juli). Preamble to the constitution of WHO. International Health Conference, New York. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution